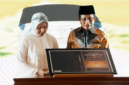Frensia.id – Anggota dewan baik pusat dan daerah sudah resmi dilantik dan ambil sumpah jabatan. Dikabarkan dari 580 anggota dewan pusat, terdapat 21,9 persen diantaranya adalah perempuan. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) seperti dilansir Kompas.com, bahwa jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan. Bahkan, pencapaian ini belum pernah ada sebelumnya.
Bertambah akumulasi perempuan di kursi legislatif di pusat ataupun di daerah memberikan angin sengar bagi masyarakat melalui produk hukum yang mereka perjuangkan. Mereka menjadi benteng untuk memperkokoh kebijakan yang lebih inklusif bagi kaum lemah, perempuan dan anak.
Hadirnya Mereka di ruang parlemen diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai eti dan moral. Bukan sebaliknya, membiarkan “kematian Tuhan” sebagai simbol aras politik yang kehilangan arah moralnya.
Istilah “kematian Tuhan” konon katanya hasil gagasan filsuf terkemuka Friedrich Nietzsche hubungannya dengan konteks modernitas, bahwa nilai-nilai religius dan etika tradisional yang terus memudar. Dalam kaitannya dengan parlemen, kematian Tuhan ini terlihat ketika setiap keputusan lebih condong mementingkan kekuasaan, kepentingan kelompok, keuntungan kantong pribadi ketimbang etika dan moral publik.
Mengesampingkan nilai-nilai moral yang semestinya mendasari setiap pengambilan keputusan politik untuk kepentingan publik adalah bentuk nyata membiarkan kematian Tuhan di parlemen. Bagaimana dengan parlemen periode lima tahun kedepan, dengan bertambahnya perempuan di kursi legislasi? mampukah mereka terus “menghidupkan Tuhan” dengan menjaga ruh etis itu ?
Atua sama saja, perempuan di parlemen juga akan ikut arus dalam kompas politik yang sama? Aneh jika hal demikian terjadi, sebab selama ini tidak sedikit perempuan yang merasa kebijakan negara bersifat patrialis dan belum akomodatif bagi perempuan dana anak.
Prodak perundang-undangan dianggapnya kental dengan patriarki (baca : menindas) bagi kaum perempuan. Disaat jumlah perempuan di parlemen bertambah, peluang mewujudkan kebijkan lebih inklusif semakin lebar pula. Tergantung kesungguhan mereka memperjuangkan idealisme tersebut, apa tidak?
Perjuangan mereka tentu tidak mudah di parlemen. Mereka diharapkan mampu memperjuangkan kebijakan hukum (legal policy) yang adil untuk semua. Namun di sisi lain, mereka adalah anggota dewan yang sedang melaju diatas kendaraan parpol pengusungnya. Mau tidak mau mereka harus patuh pada suara partai. Bagi perempuan yang komit dengan narasi tentang keadilan dan kesejahteraan, apapun itu bukanlah masalah.
Mereka tidak akan larut dalam sistem yang justru mengadaikan keadilan dan kesejahteraan yang mereka sering gaungkan. Jika Perempuan di parlemen masih ikut tawar-menawar kebijakan demi kepentingan kelompoknya, mereka membiarkan pertimbangan etis yang seharusnya berpihak pada rakyat. Dengan begitu, mereka tidak hanya mengkhianati rakyat, tapi kaum mereka sendiri, sesama perempuan.
Lebih jauh dari itu, mereka adalah bagian yang mengabaikan “kematian Tuhan” di kursi legislasi, dimana membiarkan hilangnya standar deontologis dan arah moral di ruang politik. Oleh karena itu, bertambahnya perempuan di parlemen menjadi harapan untuk menghidupkan etika dalam pengambilan keputusan. Bukankah perempuan identik dengan perhatiannya terhadap persolan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan?
Disini patut bertanya, apakah bertambahnya perempuan di parlemen yang memiliki tanggung jawab legislasi, anggaran dan pengawasan akan semakin memperkokoh nilai-nilai etis? Atau justru, bangsa ini akan hidup dalam situasi dan kondisi di mana Tuhan “telah mati” seperti yang diingatkan Nietzsche? Nilai keadilan, kebaikan, cita-cita kesetaraan dan kesejahteraan ikut terkubur? Kesemuanya hanya bisa dijawab oleh perempuan yang saat ini sedang mengabdi untuk kepentingan rakyat di ruang parlemen.*