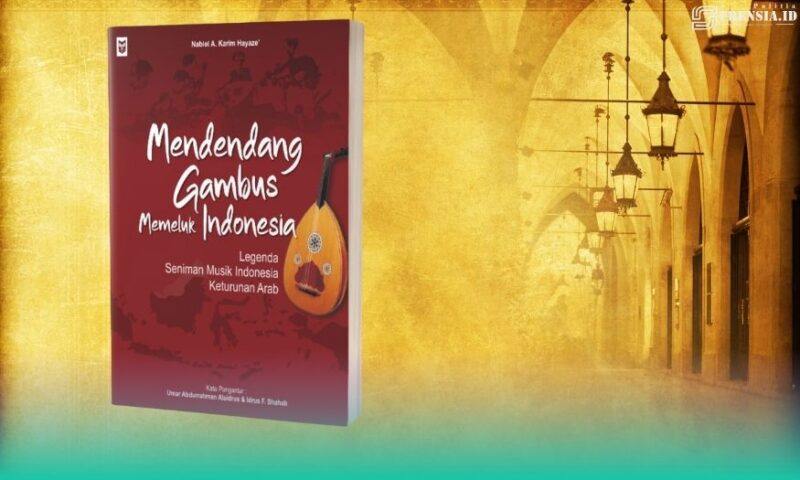Frensia.id- Ada irama yang tidak hanya terdengar oleh telinga, tetapi mampu mengetuk nurani dan menghangatkan ruang-ruang dalam hati kita. Irama yang bukan hanya bunyi, melainkan simpul ingatan, sejarah, dan identitas. Dalam buku Mendendang Gambus Memeluk Indonesia, Nabiel A. Karim Hayaze’ menyusun sebuah kisah yang mengalir seperti lagu lama yang kita dengar kembali—dan tiba-tiba terasa begitu dekat dan personal.
Buku ini adalah perayaan kecil tapi bermakna atas kontribusi para seniman keturunan Arab di Indonesia yang selama ini nyaris tak disebut dalam buku sejarah kebudayaan populer. Ia adalah simfoni kisah, penggalan biografi, dan untaian rasa syukur yang menebalkan kesadaran kita bahwa Indonesia tumbuh dari banyak suara—dan Gambus adalah salah satunya.
Sejak masa kolonial, masyarakat peranakan Arab, khususnya dari Hadramaut, Yaman, telah menetap dan menyatu dengan denyut nadi tanah air ini. Mereka tidak datang hanya membawa dagangan atau dakwah, tetapi juga kebudayaan. Salah satunya adalah musik. Gambus, musik berdawai yang berasal dari dunia Arab, perlahan namun pasti menemukan ruangnya di Indonesia.
Awalnya ia hadir dalam lingkungan tertutup, di pesta-pesta keluarga dan komunitas. Namun tak butuh waktu lama, alat musik itu mulai menyentuh publik, menyentuh akar-akar Melayu dan lambat laun bersenyawa menjadi warna baru yang sangat Indonesia.
Gambus bukan sekadar musik etnis. Ia berevolusi. Ia berinteraksi dengan musik lokal, berbaur dengan keroncong, bersentuhan dengan dangdut, bahkan ikut membentuk identitas musik populer Indonesia di era modern.
Nabiel tidak menulis dengan pendekatan akademis yang kaku. Ia bukan etnomusikolog atau kritikus musik. Ia adalah penutur cerita—penyambung suara-suara lama yang hampir padam. Buku ini bukan tentang teori musik, melainkan tentang manusia dan jejak hidup mereka.
Ia memperkenalkan kita pada sosok-sosok seperti S. Abdullah Bamuzaham, yang dikenal sebagai Bapak Keroncong Indonesia, pencipta lagu Mars PAI (Persatuan Arab Indonesia) yang sarat semangat persatuan.
Kemudian ada Syekh Albar, maestro Gambus dan ayah dari rocker Ahmad Albar. Lalu nama besar seperti Said Kelana Bawazier, seniman jazz dengan julukan “Armstrong of the East”, yang mampu meniupkan semangat dalam musik dengan terompet mautnya. Husein Mutahar juga hadir, bukan hanya sebagai penyelamat bendera pusaka, tetapi juga komponis besar pencipta lagu-lagu perjuangan yang kita nyanyikan setiap Hari Kemerdekaan.
Setiap nama dalam buku ini adalah fragmen dari mozaik besar musik Indonesia. Mereka adalah penyair, pemusik, pejuang kebudayaan. Mereka tidak sekadar bermain musik, mereka menjadikan musik sebagai jalan hidup, sebagai bahasa untuk mencintai tanah air, dan sebagai alat untuk menyampaikan siapa mereka sebenarnya. Dan mereka tidak melakukannya dengan bising, tidak dengan deklarasi besar. Mereka bekerja dalam sunyi, mengukir melodi dan lirik yang kini menjadi bagian dari memori kolektif bangsa ini.
Membaca buku ini membuat kita menyadari betapa banyak nama yang selama ini terlewatkan, dilupakan, atau bahkan tidak pernah diketahui. Seperti Fahad bin Munif, musisi muda asal Bogor yang memenangkan ajang internasional King of Oud di Arab Saudi pada 2019. Kemenangannya bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga pengakuan atas kualitas dan keberanian anak bangsa dalam membawa warisan budaya yang telah dimodernisasi tanpa meninggalkan akarnya.
Sayangnya, tak lama kemudian, Fahad meninggal dunia. Namun sebelum kepergiannya, ia sempat diwawancarai oleh Nabiel—dan dari sanalah kisahnya diabadikan dalam buku ini, menjadi suara yang tak akan hilang ditelan waktu.
Yang menarik, buku ini tidak berhenti pada tokoh-tokoh lelaki. Ia juga memberikan ruang bagi para perempuan keturunan Arab yang berkarya di dunia musik Indonesia, seperti Sorayya bin Thalib, istri dari maestro Ahmad Vad’aq, yang dikenal sebagai Umi Kalsum Indonesia.
Atau Camelia Malik, Ratu Jaipong, penyanyi dangdut yang menggebrak panggung hiburan Indonesia. Kehadiran mereka menandai bahwa kontribusi keturunan Arab dalam musik tidaklah monolitik. Ia kaya, beragam, dan menyentuh semua sisi.
Membaca buku ini tidak hanya memperkaya wawasan tentang musik, tetapi juga tentang makna Indonesia itu sendiri. Bahwa Indonesia adalah rumah dari pertemuan, bukan pemisahan. Ia adalah tempat di mana musik Arab bisa berpadu dengan nada Melayu, di mana oud bisa bersanding dengan gitar listrik, dan di mana nama-nama seperti Albar, Aidid, Bawazier, atau Mutahar bukan sekadar nama Arab, melainkan nama Indonesia juga.
Buku ini mengajarkan bahwa musik bisa menjadi bahasa pemersatu. Ia tidak bertanya dari mana kita berasal, tetapi ke mana kita melangkah bersama. Ia tidak membedakan warna kulit atau bahasa ibu, tapi merangkul semuanya dalam satu irama yang menyenangkan dan menyatukan. Dan dalam dunia yang penuh dengan perpecahan dan kebisingan identitas seperti sekarang, buku ini menjadi pengingat yang sangat relevan bahwa seni dan budaya masih bisa menjadi jembatan—dan bukan jurang.
Dalam akhir kata, Mendendang Gambus Memeluk Indonesia adalah penghormatan. Ia adalah ajakan halus untuk kembali mengenal akar, menyapa sejarah yang terlupakan, dan memberi tempat pada mereka yang telah berkontribusi dalam senyap.
Buku ini bukan hanya untuk penggemar musik, tetapi untuk siapa saja yang percaya bahwa Indonesia adalah simfoni—yang tercipta dari banyak nada, banyak alat, dan banyak tangan. Sebuah simfoni yang terus hidup, terus berkembang, dan terus memeluk siapa saja yang ingin menjadi bagian darinya.