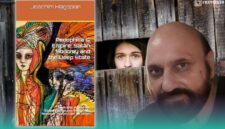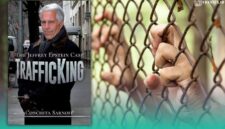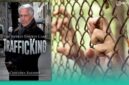Frensia.id – “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya,” sabda Nabi yang sederhana, tetapi terusir dari meja kebijakan. Dalam sabda itu, terkandung etika ekonomi Islam yang menolak eksploitasi. Tapi mari jujur: sabda ini sunyi di tengah bisingnya pertumbuhan ekonomi. Buruh tak hanya kehilangan upah, tapi juga kehilangan martabat. Hak-haknya dirampas secara sistemik oleh kekuasaan yang lebih mencintai angka ketimbang nyawa.
Jurnal berjudul “Kontekstualisasi Hadis Hak Buruh Perspektif Hermeneutika Hassan Hanafi” yang ditulis oleh Tri Mulyani, Hartati, dan Lukman Zain MS (Jurnal Studi Hadis Nusantara, Vol. 3 No. 2, 2021), menyuguhkan cara pandang segar atas hadis tersebut. Dengan pendekatan hermeneutika Hassan Hanafi, hadis tidak diposisikan sebagai teks beku yang tinggal disalin, tetapi sebagai teks hidup yang harus ditafsirkan dalam denyut realitas sosial.
Pendekatan Hanafi menempatkan tiga pijakan penting: kritik historis, kritik eidetis, dan kritik praksis. Kritik historis mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya menyampaikan hadis itu, tetapi pernah menjadi pekerja upahan di bawah Sayyidah Khadijah. Hadis ini tidak lahir dari langit kekuasaan, tetapi dari bumi pengalaman. Ini bukan sabda elitis, melainkan suara pekerja.
Kritik eidetis mengurai bahwa kata ajr dalam hadis bukan semata “upah”, tetapi juga mencakup ganjaran, penghargaan, bahkan kehormatan. Pekerja adalah manusia yang layak diakui kontribusinya, bukan sekadar alat produksi. Pembayaran upah, dalam terang ini, bukan semata transaksi ekonomi, tetapi peneguhan nilai keadilan.
Puncaknya adalah kritik praksis. Di sinilah tafsir agama menjelma aksi sosial. Hadis tidak berhenti di mimbar, tetapi bergerak ke meja kebijakan, ke regulasi, bahkan ke jalan-jalan tempat buruh meneriakkan haknya. Hermeneutika Hanafi mendorong teks untuk berpihak. Dalam kasus buruh, berpihak berarti menolak eksploitasi yang disahkan oleh negara.
Sayangnya, negara justru memilih jalan sebaliknya. UU Cipta Kerja yang lahir tahun 2020 adalah bukti bahwa negara lebih tunduk pada logika investasi ketimbang etika keadilan. Pemangkasan pesangon, fleksibilitas kontrak, pelemahan serikat pekerja, hingga penghapusan cuti-cuti sosial menunjukkan betapa buruh dijadikan ongkos pertumbuhan ekonomi.
Melalui kerangka Hassan Hanafi, dapat ditegaskan bahwa hadis tidak bisa dibaca tanpa konteks struktur sosial yang timpang. Ketika buruh ditindas secara sistemik, maka membaca hadis tanpa berpihak adalah pengkhianatan terhadap semangat Nabi. Agama tidak hadir untuk menenangkan yang tertindas agar sabar, tetapi untuk membangkitkan mereka agar menuntut hak.
Buruh adalah wajah manusia biasa yang menghadapi sistem tidak biasa. Maka pembacaan hadis tentang buruh harus melampaui literalitas. Ia harus menjadi panggilan moral bagi pengambil kebijakan, para pemilik modal, dan juga kalangan agamawan. Jika tidak, jangan salahkan bila hadis itu tinggal jadi hiasan, sementara keringat buruh terus mengering tanpa dibayar.