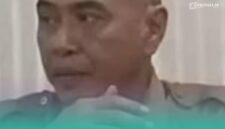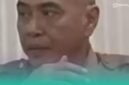Frensia.id – Ijazah palsu menjadi perbincangan hangat pasca adanya gugatan dari para pihak yang mempertanyakan ijazah Joko Widodo. Belum reda kontroversi itu, publik juga kembali dihebohkan dengan tudingan serupa terhadap Gibran Rakabuming Raka.Namun, tulisan ini tidak sedang menghakimi keaslian ijazah dua orang itu. Ada hal yang lebih penting untuk dikritisi: mengapa negeri ini begitu sibuk memperdebatkan selembar ijazah, sementara jutaan pemilik ijazah asli justru kesulitan mendapat pekerjaan?
Pertanyaan ini membuka ironi yang lebih dalam. Ijazah di negeri ini memang masih menjadi syarat formal yang sangat menentukan. Hampir semua instansi, baik negeri maupun swasta, mewajibkan pelamar kerja menyertakan ijazah minimal SMA atau sederajat. Maka, banyak anak muda rela sekolah sambil bekerja, bahkan kuliah sambil mengais rezeki, demi mengantongi ijazah yang sah. Ijazah itu adalah simbol perjuangan panjang—sebuah legitimasi bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan yang lebih baik.
Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu demikian. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 4,76% atau 7,28 juta orang. Lulusan SMK mencatat pengangguran tertinggi 9,01%, disusul SMA 7,05%. Sementara D4-S1 5,25%, DI-DIII 4,83%, SMP 4,11%, dan SD 2,32%. Data ini menunjukkan paradoks pendidikan tidak menjamin pekerjaan.
Situasi ini semakin terasa pahit, jika desas-desus tentang orang-orang yang dengan mudah membeli ijazah palsu itu benar adanya. Mereka tidak pernah mengikuti proses belajar, tidak pernah membaca tumpukan buku, bahkan tidak perlu bersusah payah mengerjakan skripsi.
Cukup membayar sejumlah uang, mereka sudah bisa mengantongi selembar kertas yang tampak sah secara administratif. Lebih ironis lagi, ada kekhawatiran bahwa sistem birokrasi kita sering kali tidak cukup cermat membedakan antara yang asli dan yang palsu.
Paradoks pun lahir. Mereka yang belajar sungguhan justru tersisih, sementara mereka yang menempuh jalan pintas dengan ijazah palsu bisa melenggang. Bagi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja demi membiayai kuliahnya, kenyataan ini sungguh menyakitkan. Perjuangan mereka seakan tidak dihargai, karena negara sendiri tidak mampu melindungi makna sebuah ijazah.
Tentu kita tak mau berlama-lama mengurai ijazah palsu ini. Namun, perlu kita sadari bahwa membiarkan hal ini dianggap sebagai masalah yang tidak penting juga jelas keliru. Membiarkan sama saja dengan menempatkan ijazah sebagai sesuatu yang “tidak penting-penting amat”. Padahal, pada sisi lain dunia kerja kita masih mensyaratkan ijazah sebagai pintu masuk utama.
Jika dilihat lebih dekat, dampak negatif dari pembiaran kasus ijazah palsu ini setidaknya dalam tiga aspek. Pertama, aspek moralitas pendidikan. Jika ijazah palsu dianggap lumrah, maka pesan yang tersampaikan ke generasi muda adalah bahwa jalan pintas lebih dihargai daripada proses. Ini bisa merusak etos belajar, mengikis budaya akademik, dan melahirkan generasi oportunis.
Kedua, aspek integritas birokrasi dan kepemimpinan publik. Bayangkan jika pejabat publik, politisi, atau pegawai negeri terbukti memakai ijazah palsu, lalu tidak ada tindakan tegas. Hal ini akan menggerogoti legitimasi hukum dan mencederai kepercayaan publik. Rakyat akan bertanya: bagaimana mungkin orang yang memimpin justru mendasarkan kariernya pada kebohongan?
Ketiga, aspek keadilan sosial dalam dunia kerja. Pemilik ijazah asli yang telah berjuang keras berpotensi tersingkir oleh pemegang ijazah palsu yang mungkin lebih berani, lebih punya akses, atau lebih pandai bermanuver.
Akhirnya, prinsip fair equality of opportunity sebagaimana ditegaskan John Rawls runtuh. Kesempatan yang seharusnya setara menjadi timpang karena negara membiarkan pemalsuan.
Narasi “yang penting skill, bukan ijazah” sering digaungkan untuk meremehkan arti pendidikan formal. Tetapi argumen ini tidak sepenuhnya benar. Skill memang penting, tetapi tanpa ijazah, skill itu sering kali tidak diakui dalam sistem resmi. Tidak ada dokter yang boleh berpraktik tanpa ijazah medis, tidak ada advokat yang boleh beracara tanpa ijazah hukum. Ijazah memberi akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi skill itu sendiri.
Karena itu, masalah utamanya bukanlah “ijazah tidak penting”, melainkan bagaimana negara dan masyarakat menempatkan ijazah secara adil. Negara perlu memperkuat sistem verifikasi ijazah, melakukan audit rutin terhadap pejabat publik, dan mengedepankan kompetensi dalam rekrutmen kerja.
Pada akhirnya, ijazah palsu bukan sekadar kasus hukum. Ia adalah cermin dari sistem sosial yang retak—sistem yang membiarkan perjuangan pendidikan sejati kalah oleh kepalsuan. Misteri dunia kerja di negeri ini tidak akan terurai jika negara gagal menjaga makna ijazah. Selembar kertas itu semestinya menjadi simbol jerih payah, bukan komoditas yang diperjualbelikan di pasar gelap.
Ijazah asli harus kembali bergigi. Jika tidak, anak-anak bangsa yang belajar dengan keringat dan air mata akan terus dikhianati oleh sistem yang lebih percaya pada kepalsuan daripada pada perjuangan.