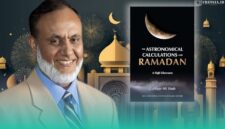FRENSIA.ID-Sebuah studi antropologis yang mendalam dan provokatif datang dari Samuli Schielke, peneliti dari Zentrum Moderner Orient (ZMO) Berlin, yang menyoroti sisi manusiawi dari praktik keagamaan yang sering kali tersembunyi di balik narasi kesalehan formal.
Dalam risetnya yang berjudul Being good in Ramadan: ambivalence, fragmentation, and the moral self in the lives of young Egyptians yang dipublikasikan di Journal of the Royal Anthropological Institute (2009), Schielke tidak hanya tentang Islam dari sudut pandang teologis yang kaku, melainkan membedah realitas sosial para pemuda di sebuah desa bernama Nazlat al-Rayyis di Mesir Utara.
Riset ini menjadi sangat menarik karena ia menantang asumsi umum akademisi yang sering menggambarkan subjek Muslim sebagai individu yang senantiasa disiplin dan berjuang menuju kesempurnaan moral, padahal kenyataan di lapangan jauh lebih berwarna, penuh negosiasi, dan fragmentasi.
Pintu masuk analisis Schielke adalah fenomena yang sangat spesifik namun sarat makna: sepak bola di bulan Ramadan. Di desa tersebut, setiap sore menjelang berbuka puasa, lapangan-lapangan dipenuhi oleh para pemuda yang bermain bola dengan intensitas tinggi. Bagi pengamat awam, mungkin ini terlihat sebagai sekadar hobi atau cara mengisi waktu “ngabuburit”.
Namun, Schielke menemukan makna yang lebih dalam. Berdasarkan interaksinya dengan para pemuda setempat, sepak bola di bulan suci berfungsi sebagai mekanisme pertahanan moral. Salah satu informan Schielke secara gamblang menyatakan bahwa bermain bola adalah cara paling efektif untuk menghindari dosa.
Jika mereka tidak bermain bola, waktu luang tersebut berpotensi digunakan untuk aktivitas yang dianggap haram, seperti menggoda perempuan, merokok ganja, atau meminum alkohol. Dengan demikian, olahraga menjadi ruang “netral” yang menjaga kesucian puasa mereka di tengah godaan gaya hidup muda-mudi yang meledak-ledak.
Temuan ini mengantarkan Schielke pada inti argumennya tentang ambivalensi moral. Ia mengangkat sebuah peribahasa lokal yang sangat populer di kalangan pemuda Mesir, yakni “Satu jam untuk hatimu, satu jam untuk Tuhanmu” (sa’a l-qalbak w-sa’a l-rabbak).
Frasa ini merupakan sebuah strategi hidup. Para pemuda ini tidak melihat diri mereka sebagai orang suci, namun juga menolak disebut pendosa. Mereka membagi waktu dan ruang kehidupan mereka ke dalam kompartemen-kompartemen yang terpisah.
Ramadan adalah “waktu untuk Tuhan” yang bersifat sakral dan temporer, sebuah periode di mana mereka berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ketaatan total selama satu bulan ini, menurut analisis Schielke, secara paradoks berfungsi untuk melegitimasi atau “menebus” perilaku yang kurang religius di sisa sebelas bulan lainnya.
Ada semacam logika moral di mana kesalehan intensif di bulan suci memberikan “izin” psikologis untuk kembali menikmati kesenangan duniawi setelahnya.
Dinamika ini mencapai puncaknya pada momen transisi menuju Idul Fitri. Schielke melukiskan perubahan atmosfer desa yang drastis begitu matahari terakhir Ramadan terbenam. Apa yang disebut sebagai kemenangan spiritual segera berganti menjadi perayaan kebebasan duniawi. Jalanan kembali dipenuhi oleh hiruk-pikuk yang sebelumnya diredam; penjualan narkotika jenis ganja kembali marak, bioskop dan kafe memutar film-film yang menampilkan sensualitas, dan interaksi lawan jenis menjadi lebih terbuka. Schielke menceritakan pengamatannya di malam Idul Fitri, di mana sekelompok pemuda di kafe menertawakan orang-orang tua yang menonton tayangan dewasa, sebuah tindakan yang menandai kembalinya mereka ke “normalitas” yang mencakup kenakalan-kenakalan remaja. Idul Fitri, dalam kacamata ini, bukan hanya hari raya keagamaan, tetapi juga sinyal bahwa “jam untuk Tuhan” telah usai dan “jam untuk hati” (kesenangan) telah dimulai kembali.
Melalui riset ini, Schielke menawarkan pandangan bahwa ketidakkonsistenan ini bukanlah bentuk kemunafikan, melainkan sebuah fragmentasi diri yang wajar dalam modernitas. Pemuda-pemuda di Nazlat al-Rayyis hidup di tengah persimpangan berbagai “daftar moral” yang saling berkompetisi—tuntutan agama, desakan ekonomi kapitalis, hasrat konsumerisme, dan ekspektasi sosial tradisional.
Mereka terus-menerus bernegosiasi dengan diri mereka sendiri, mencoba menyeimbangkan ketakwaan dengan keinginan untuk menikmati masa muda. Riset Schielke pada akhirnya mengajak kita untuk lebih empatik dalam melihat fenomena keberagamaan; bahwa di balik cita-cita kesalehan yang tinggi, terdapat manusia biasa yang bergulat dengan ambiguitas, keraguan, dan keinginan duniawi yang sangat manusiawi.
Penulis : Mashur Imam