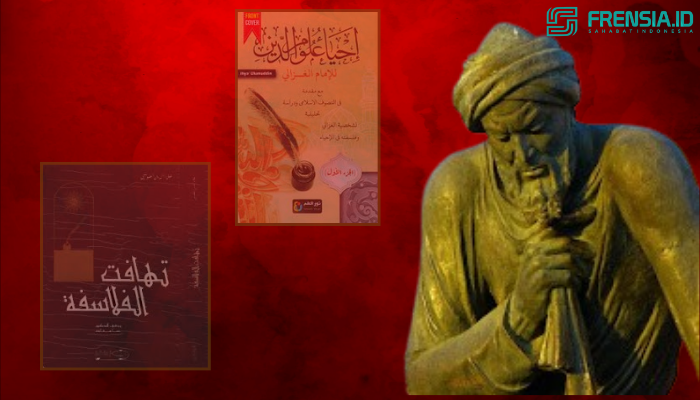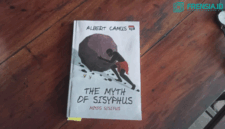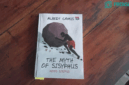Frensia.id- Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia nama Al-Ghazali terbagi menjadi dua. Seolah mempunyai wajah yang sama tetapi dapat dilihat dari dua sisi berbeda, yang mana setiap sisi menampilkan sesuatu yang tidak tampak dari sisi yang lain, begitu juga sebaliknya.
Seperti inilah, bagaimana imam besar tasawuf kalangan Sunni difahami dan dipelajari oleh kalangan cerdik cendekia di Indonesia yang diakomodasi oleh lembaga pendidikan.
Sebagaimana diketahui, secara garis besar instansi pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian, pertama pendidikan tradisional, yaitu pesantren dan pendidikan modern, yaitu sekolah dari tingkat dasar hingga universitas.
Bagi lembaga pendidikan modern Al-Ghazali lebih dikenal sebagai seorang filosof dengan kitabnya Maqasid Al-Falasifah dan Tahafut Falasifah (kerancuan filsafat).
Bagi lembaga pendidikan pesantren nama Al-Ghazali akan lebih dikenal sebagai seorang sufi, dengan kitab yang diajarkan Ihya’ Ulumiddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah.
Sekalipun demikian dari kedua lembaga pendidikan diatas, sebenarnya sama-sama mengetahui bahwa Al-Ghazali adalah seorang filosof dan sufi sekaligus.
Memang dalam pengetahuan Al-Ghazali adalah seorang yang mahir akan kedua disiplin ilmu tersebut.
Didahului dengan kajian filsafat kemudian pada tasawuf. Sebagai seorang intelektual ia merupakan pribadi yang sangat mewah.
Di Pesantren kitab-kitab karangan Al-Ghazali banyak di kaji, hanya saja yang meliputi tema tasawuf, mulai dari tataran paling dasar seperti bidayatul hidayah hingga yang paling spektakuler ihya’ ulumiddin.
Pesantren di Indonesia notabene berfaham Sunni, yang mana menjadikan sosok Al-Ghazali sebagai imam atau panutan dalam persoalan tasawuf.
Oleh karena itu, tidak aneh kiranya jika Imam kelahiran Tus, Khurasan ini cukup populer, bahkan lebih menonjol dari beberapa pakar tasawuf lainnya, sekalipun sama-sama dianut.
Di dunia pesantren, sebenarnya cukup mengenal mengenai cakupan disiplin ilmu yang dikuasai Al-Ghazali, termasuk filsafat.
Tetapi kajian yang mendayagunakan akal tersebut tidak dipelajari secara khomprensif atau masuk dalam kurikulum pesantren, karena orientasi dari mata pelajaran tertuju pada disiplin ilmunya, bukan kepada pemikiran sosoknya.
Dengan demikian, maka pribadi Al-Ghazali yang juga mempunyai kepakaran di bidang filsafat tidak secara sistematis dipelajari, hanya sekedar diketahui saja akan identitasnya atau di baca secara persoanal oleh segelintir santri saja.
Begitu pula dengan sosok Al-Ghazali yang dikenal di Universitas, nama besarnya lebih menonjol dengan popularitasnya sebagai seorang ahli filsafat. Bersanding dengan para ahli filsafat, seperti Al-Kindi, Ibn Sina dan Al-Farabi.
Budaya kampus yang menjadikan kebebasan sebagai trademark, turut serta dalam mendukung ketenaran Al-Ghazali sebagai seorang filsuf. Dimana salah satu nyawa dari filsafat adalah kebebasan itu sendiri.
Sama halnya dalam dunia pesantren, di Universitas filsafat merupakan mata kuliah dasar yang dipelajari di semua jurusan, sehingga menjadikan disiplin ini dikenal oleh secara familiar oleh semua mahasiswa.
Selain itu beberapa komunitas diskusi juga menerapkan kurikulum dengan memasukkan kajian filsafat sebagai salah satu programnya. Berbeda sekali dengan tasawuf, yang mana secara organik tidak terdapat perhatian.
Oleh karena itu sosok AL-Ghazali sebagai seorang yang mengambil peran untuk memberi komentar terhadap pandangan-pandangan filsuf yang lain dan mengarang buku tentang tema-tema tersebut, tidak bisa dilepaskan untuk menjadi pembahasan.
Suasana akademis yang berbeda inilah, yang menjadikan polarisasi terhadap wajah Al-Ghazali secara opsional. Sekalipun dari masing-masing sudut pandang turut serta sama-sama mengakui kepakarannya dari dua disiplin tersebut.