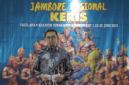Frensia.id – Asal garam tiba di nasi, apa pun dikerjakan. Ungkapan yang cocok mengambarkan pilkada tahun ini, tak penting caranya bagaimana mereka lakukan untuk mencapai hajat politiknya, menjadi kepala daerah. Salah satunya, mengaku paling dekat dengan pemerintah pusat. Tak jarang dalam kampanye masyarakat selalu disodorkan dengan retorika yang menggembar-gemborkan kedekatannya dengan pemerintahan nasional.
Bahkan dalam debat publik narasi ngaku paling dekat pemerintah pusat selalu menjadi jurus andalannya. Sebut saja dalam pilkada Jawa timur, Jember misalnya. Salah seorang calon bupati, dari debat pertama hingga terakhir, tak henti-hentinya membawa nama besar orang nomor satu di republik ini, Prabowo Subianto.
Pesannya jelas: dirinya, sebagai kader partai yang diusung oleh ketua partai dan saat ini mengabdi sebagai presiden. Dianggap punya akses istimewa untuk menyelaraskan serta mensinergikan kepentingan daerah dengan kebijakan pusat.
Retorika ini, menyampaikan pesan tersirat bahwa hanya dirinya “satu-satunya” kandidat yang mendapatkan “restu dan dukungan langsung” dari pemerintah pusat dan akan membawa kemajuan daerah. Seolah pucuk pimpinan nasional hanya mau bersinergi atau mengistimewakan paslon tersebut memakmurkan rakyat.
Namun, apakah benar kedekatan dengan partai tertentu menggaransi sinergi, kepentingan rakyat dan kemajuan daerah terwujud? Atau sebaliknya, narasi ngaku ini justru mengesampingkan esensi utama seorang pemimpin lokal, melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang partai atau golongan?
Narasi ngaku paling dekat ini menciptakan beberapa masalah yang tidak mai-main dan dianggap sepele. Pertama, calon kepala daerah – bupati dan gubernur—membangun ilusi bahwa pemerintah pusat hanya akan mengutamakan pada kepala daerah dari partai atau koalisi yang sama. Sebuah pendirian yang tidak selaras dengan prinsip dasar negara, melayani seluruh rakyat tanpa pengecualian.
Kedua, kondisi ini mereduksi esensi demokrasi. Beberapa esensi yang terciderai, kesetaraan peluang, kompetisi berbasis gagasan, kedaulatan rakyat terpengaruh bukan karena gagasan dan netralitas pemerintah. Pilkada yang seharusnya kompetensi ide dan program menjadi ajang mempertontonkan kedekatan personal.
Ketiga, pengakuan dekat tersebut juga mengundang kebingungan masyarakat, seolah-seolah terkesan keberpihakan pemerintah pusat adalah hak istimewa yang dimonopoli oleh pasangan dan partai tertentu. Masyarakat akan merasa was-was, ini yang disebut diatas kedaulatan rakyat terpengaruh bukan karena gagasan.
Jika kandidat calon kepala daerah tak henti-hentinya mengklaim punya kedekatan dan “akses khusus” dengan pemerintah pusat, pertanyaan mendasarnya adalah kepada siapa negeri ini sebenarnya mengabdi ? Apakah pemerintah pusat enggan untuk bersinergi jika kepala daerah yang terpilih bukan dari partai atau koalisinya? Kepentingan rakyat hanya ilusi jika demikian? Bukan kepada rakyat lagi negeri ini mengabdi, namun hanya kolaborasi kepentingan elit saja.
Bagaimana dengan pemerintah pusat, akankah mereka terbuka bersinergi membangun negeri ini, siapapun calon kepala daerahnya? Rakyat Indonesia, hingga kini masih terngiang-giang sumpah presiden Prabowo Subianto untuk berbakti pada negara dan bangsa.
“Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami.” Sumpah Prabowo Subianto, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Minggu, 20 Oktober 2024
Dalam etika demokrasi, pemimpin negeri ini harus memiliki tanggung jawab mendukung agenda pembangunan di semua daerah terlepas dari partai dan golongannya. Seperti sumpah Presiden Prabowo Subianto, akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, calon kepada daerah yang kerap kali mengaku dirinya akan mudah menyelaraskan program pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat, secara tidak langsung melukai sumpah presiden itu sendiri. Selain itu, cita-cita luhur bernegara melayani masyarakat secara inklusif akan tereduksi.
Masyarakat menaruh optimis kepada pemerintah pusat, mereka akan bersingersi dengan kepala daerah tanpa memandang siapapun mereka, apapun partai dan koalisinya. Tidak ada narasi kader partai, pimpinan atau partai koalisi yang mengusung saat ini menjadi pucuk pimpinan pemerintah pusat, ketika semuanya dilantik titik akhirnya mengabdi untuk kepentingan rakyat.
Etika bernegara semacam ini sudah diingatkan oleh Bung Hatta bahwa kepemimpinan bukan tentang kedekatan dengan kekuasaan, tetapi keberanian menjadi penyuluh harapan rakyat.
“Membangun Indonesia yang adil dan Indonesia makmur harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab serta keberanian menghadapi segala kesukaran. Pokok kemauan dan keberanian itu terletak pada cinta akan kebenaran dan keadilan, sebagai pembawaan orang berilmu cinta akan suatu cita-cita besar yang menjadi penyuluh harapan bangsa”. Bung Hatta, seperti dikutip dari Tempo.co.
Sebagai komitmen membangun kesetaraan dalam berpilkada, memberikan keleluasaan berpikir bagi masyarakat, narasi ngaku paling dekat ini seharusnya dihentikan. Masyarakat tak perlu khawatir, siapapun yang terpilih, pemerintah pusat akan on the track mengabdi untuk rakyat.
Sinergi adalah kewajiban institusional, bukan keistimewaan kedekatan personal. Pemerintah Pusat harus setia pada sumpahnya, tak tebang pilih siapa kepala daerahnya, ada juta rakyat yang wajib diurus. Begitu juga bagi masyarakat, ia harus kritis. Tidak terkecoh pada jargon “kedekatan” dengan pihak tertentu, pilihlah dengan visi-misi, program yang realistis, serta dengan nurani yang bersih.