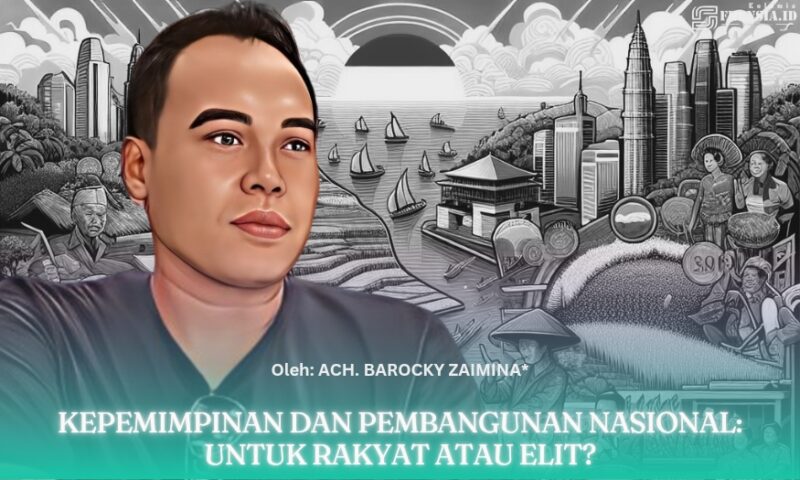Oleh : ACH. BAROCKY ZAIMINA*
Frensia.id- Di tengah gempita pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan bangsa, satu pertanyaan fundamental terus bergema: untuk siapa sebenarnya proyek-proyek raksasa itu dibangun? Apakah kepemimpinan nasional benar-benar berakar pada aspirasi rakyat, ataukah sekadar memperkokoh oligarki yang semakin terinstitusionalisasi dalam tubuh negara?
Selama satu dekade terakhir, pembangunan fisik menjadi mantra utama dalam narasi kepemimpinan nasional. Jalan tol melintasi pulau, pelabuhan dan bandara diperluas, dan kini, Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan ke Kalimantan dengan klaim desentralisasi kekuasaan dan transformasi hijau.
Namun, analisis kritis terhadap arah dan dampak pembangunan ini mengungkap paradoks: di balik kemegahan proyek-proyek strategis nasional (PSN), terhampar ketimpangan struktural yang kian dalam.
Secara teoritik, pembangunan ideal adalah pembangunan yang inklusif dan partisipatif, sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen dalam konsep development as freedom bahwa pembangunan sejati adalah pelebaran kebebasan dan kapabilitas manusia. Namun, dalam praktik di Indonesia, pembangunan sering kali beroperasi dalam logika developmentalisme otoritarian, di mana negara bertindak sebagai agen utama pembangunan, tetapi tanpa mekanisme partisipasi yang memadai dari warga.
Proyek-proyek PSN, meski diklaim sebagai jalan pemerataan, justru acap kali menimbulkan eksklusi sosial. Masyarakat adat kehilangan tanah ulayat tanpa konsultasi bermakna (free, prior, and informed consent), petani tergusur tanpa skema resettlement yang adil, dan warga kota miskin mengalami penggusuran atas nama “penataan kawasan”.
Di sinilah terlihat bahwa pembangunan bukan netral secara politik, melainkan memiliki bias kelas dan kekuasaan. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori elit capture, yaitu proses di mana kebijakan publik dibajak oleh kepentingan segelintir elit baik politisi, birokrat, maupun pengusaha.
Dalam konteks IKN, misalnya, keterlibatan konsorsium besar dengan insentif fiskal dan kemudahan regulasi menunjukkan gejala klasik public-private collusion. Menurut musabab ini, negara tidak lagi bertindak sebagai pengatur yang netral, tetapi sebagai fasilitator bagi akumulasi kapital elit.
Douglas North dalam institutional economics menyebut kondisi semacam ini sebagai limited access order, yakni situasi ketika akses terhadap sumber daya dan peluang hanya terbuka bagi kelompok terbatas yang memiliki relasi kuasa. Negara menjadi arena patronase, bukan pelayanan publik.
Pemindahan IKN ke Kalimantan kerap dirayakan sebagai simbol desentralisasi. Namun, pertanyaannya: apakah pemindahan geografis juga berarti redistribusi kuasa dan kesejahteraan? Tanpa transformasi struktural, pemindahan pusat pemerintahan justru hanya memindahkan ketimpangan—dari Jakarta ke titik baru yang lebih terisolasi dari partisipasi rakyat.
Bahkan, dalam konteks urban political economy, kota baru seperti IKN rentan menjadi ruang akumulasi baru bagi modal, sebagaimana diulas oleh David Harvey dalam konsep accumulation by dispossession di mana pembangunan dijadikan dalih untuk pengambilalihan tanah dan sumber daya demi kepentingan akumulasi kapital.
Kepemimpinan nasional seharusnya berpijak pada amanat konstitusi: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ketika kebijakan lebih sering dibahas dalam ruang tertutup antara elite ekonomi dan politik, dan rakyat hanya menjadi objek “simulasi partisipasi”, maka apa yang kita hadapi bukanlah demokrasi substansial, melainkan oligarkhi terkelola.
Sebagaimana dikemukakan oleh Guillermo O’Donnell dalam konsep delegative democracy, demokrasi di banyak negara berkembang justru menghasilkan pemimpin yang bertindak seolah mendapat mandat tak terbatas pasca pemilu. Kebijakan menjadi domain teknokratik yang dijauhkan dari deliberasi publik.
Pembangunan IKN dan berbagai proyek infrastruktur lainnya juga mengabaikan aspek ekologis yang krusial. Penggundulan hutan tropis di Kalimantan tidak hanya berdampak pada krisis keanekaragaman hayati, tetapi juga memicu krisis iklim yang lebih luas.
Pandangan ecological modernization yang melihat bahwa pembangunan bisa berjalan berdampingan dengan kelestarian lingkungan tampaknya hanya sebatas retorika, bukan praktik yang diterapkan dengan sungguh-sungguh.
Di sisi lain, masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan alam justru dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Hak atas ruang hidup mereka digantikan dengan dokumen amdal yang penuh jargon teknis, yang lebih melayani investor ketimbang keberlangsungan komunitas lokal.
Pembangunan seharusnya tidak hanya menjadi urusan teknis infrastruktur, tetapi juga persoalan redistribusi kekuasaan dan sumber daya. Teori politics of redistribution dari Nancy Fraser dan Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa ketimpangan tidak akan selesai hanya dengan menyediakan fasilitas, tetapi dengan mengubah struktur akses terhadap modal sosial, budaya, dan ekonomi.
Tanpa pendekatan redistributif yang nyata, pembangunan hanya akan menjadi arena penguatan kekuasaan elite sementara rakyat kecil terus-menerus berada di tepi. Kesetaraan hanya mungkin lahir bila negara berani mengambil posisi tegas untuk membatasi dominasi modal dalam proses kebijakan.
Beberapa wilayah di Indonesia sejatinya telah menunjukkan model pembangunan berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan dan partisipatif. Mulai dari inisiatif desa adat dalam mengelola hutan hingga koperasi rakyat yang tumbuh dari solidaritas ekonomi lokal.
Sayangnya, pendekatan ini kerap dipinggirkan karena tidak selaras dengan narasi besar “pertumbuhan tinggi” yang diusung negara. Justru dari pinggiran inilah, model pembangunan yang membumi dan merata dapat dihidupkan.
Kepemimpinan nasional harus berani melihat dan belajar dari inisiatif-inisiatif mikro yang selama ini diabaikan oleh makro-strategi pembangunan nasional. Salah satu problem serius pembangunan saat ini adalah dominasi teknokrasi tanpa kepekaan etis.
Banyak kebijakan dirancang berdasarkan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) semata, tanpa mempertimbangkan implikasi etika terhadap kelompok rentan. Ketiadaan moral economy dalam perumusan kebijakan inilah yang membuat pembangunan kehilangan wajah manusianya.
Pembangunan yang melupakan keadilan sosial akan selalu menghasilkan ketimpangan, betapapun canggihnya alat ukur pertumbuhan yang digunakan. Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar birokrat ahli, tetapi negarawan dengan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Kita tidak sedang menolak pembangunan.
Yang menjadi sorotan adalah siapa yang menentukan arah pembangunan, siapa yang terlibat, dan siapa yang mendapat manfaat. Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, indeks investasi, atau jumlah proyek, tetapi dari indikator kesejahteraan rakyat marjinal: akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hak atas tanah, dan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan.
Kepemimpinan yang berpihak pada rakyat adalah yang mampu menantang logika pembangunan eksklusif ini. Ia harus berani melibatkan warga dalam perencanaan, mengedepankan keadilan redistributif, dan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama, bukan efek samping dari pertumbuhan ekonomi.
Arah kepemimpinan nasional saat ini berada di titik genting: apakah akan menjadi pelayan rakyat yang visioner atau sekadar manajer proyek yang teknokratis? Sejarah tidak mencatat jumlah proyek atau investor yang hadir, melainkan siapa yang dibela ketika kekuasaan berada di tangan. Kepemimpinan sejati bukan ditentukan oleh megahnya bangunan, tetapi oleh keberanian berpihak pada mereka yang selama ini disingkirkan dari meja kekuasaan.
Penulis : *Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kiyai Achmad Shiddiq Jember dan Aktif sebagai Praktisi Sosial Pendidikan dan Ekonomi Kerakyatan